Diskriminasi terhadap ilmuwan kembali jadi topik hangat, bukan cuma di obrolan warung kopi, tapi juga di media sosial dan di kalangan akademisi sendiri. Yang bikin miris, banyak keluhan soal artikel ilmiah yang ditolak mentah-mentah oleh jurnal-jurnal keren dari negara maju, cuma gara-gara penulisnya berasal dari universitas di negara berkembang atau, lebih parah lagi, dari kelompok minoritas. Praktik kayak gini jelas bikin kita bertanya-tanya: seadil apa sih dunia publikasi ilmiah ini?
Diskriminasi: Ada Apa di Balik Pintu Jurnal Ilmiah?
Jurang Publikasi dan Dana Penelitian
Coba deh tengok hasil studi di jurnal The Lancet Regional Health – America (2025). Francisco Jiménez-Trejo dan timnya menemukan adanya rasisme yang sudah mengakar dalam sistem ilmiah. Bayangin aja, ada perbedaan mencolok antara jumlah penelitian yang diterbitkan dari negara miskin dan negara kaya. Gak cuma itu, dana penelitian juga lebih banyak ngalir ke ilmuwan kulit putih dibandingkan ilmuwan Afrika-Amerika. Para peneliti sampai bilang ini darurat kesehatan masyarakat global!
Rasisme dari Sudut Pandang Budaya dan Teori
Sementara itu, Kathomi Gatwiri dkk. di jurnal Sociology Compass (2025) nemuin hal yang gak kalah bikin geleng-geleng kepala. Karya-karya peneliti yang pakai sudut pandang budaya, teori, atau politik yang “terpinggirkan” sering banget kena rasisme. Ini paling sering dialami sama akademisi Afrika-Amerika atau masyarakat adat. Mereka dapet data ini dari wawancara mendalam dengan 23 akademisi dari 14 universitas di Australia. Mereka semua peneliti dari ras dan budaya minoritas di berbagai bidang ilmu.
Curhat Para Peneliti Korban Rasisme
Peer Review yang Berat Sebelah
Salah satu bentuk rasisme yang paling sering muncul adalah bias di sistem tinjauan sejawat (peer review). Harusnya, sistem ini jadi benteng terakhir buat mastiin kualitas penelitian. Tapi, nyatanya malah jadi arena diskriminasi. Para peneliti yang jadi responden studi itu bilang, umpan balik yang mereka terima seringkali pedas dan gak ngebangun sama sekali.
Kasus Nyata: Artikel Ditolak karena Rasisme
Billy, salah satu responden, cerita pengalamannya pas ngirim ulasan ke Medical Journal of Australia tentang sebuah karya yang dia anggap rasis. “Tulisan saya ditolak, tapi saya banding atas permintaan editor. Balasannya? ‘Kami menolak banyak kiriman. Kami gak wajib ngasih penjelasan ke siapapun’. Gitu doang!” ungkap Billy dalam artikel berjudul “Maintaining Standards or Gatekeeping the Academy? Reflections of Peer Review Experiences by Racially and Culturally Minoritized Scholars in Australia,” yang terbit 22 Agustus 2025. Billy menambahkan, “Buat saya, ada udang di balik batu. Kami gak mau berurusan sama rasisme di profesi medis.”
Kata Billy, diskriminasi rasial ini bisa kejadian secara terang-terangan atau halus. Misalnya, peneliti minoritas dituntut buat kerja ekstra keras buat nunjukkin relevansi karya mereka.
Peer Review: Idealnya Gimana, Realitanya?
Sistem peer review ini kan harusnya jadi fondasi buat ngejaga standar dan kualitas penelitian. Para reviewer bertugas buat validasi, ngevaluasi, dan ningkatin ketelitian penelitian. Tapi, kenyataannya? Banyak reviewer yang kerja sukarela ini rentan sama bias, subjektivitas, inkonsistensi, dan kritik yang gak adil. Parahnya lagi, risiko-risiko ini sering dianggap wajar dalam proses peer review.
Lawan! Gimana Caranya?
Taktik Bertahan Para Peneliti Minoritas
Ngadepin rasisme ini, para peneliti punya berbagai cara. Ada yang milih buat ngikutin aja arus dan norma-norma kaku di industri publikasi. Angela, contohnya, milih buat punya publikasi yang lebih sedikit daripada ngasilin karya yang kualitasnya abal-abal. “Saya gak terlalu banyak nerbitin karya beberapa tahun terakhir. Karya yang saya hasilkan gak akan masuk ke jurnal berdampak tinggi yang, ketika mereka lihat peringkatnya, akan masuk ke jurnal niche,” kata Angela. “Saya gak akan ngubah apapun sekarang. Saya lebih milih ninggalin dunia akademis daripada jadi sesuatu yang gak saya suka atau main-main dengannya,” tambahnya.
Berani Melawan Hegemoni Peer Review
Ada juga peneliti yang milih buat ngelawan hegemoni peer review. Caranya? Ngajuin pertanyaan-pertanyaan provokatif ke reviewer. Ada juga yang jadi reviewer suportif dan kolaboratif, nganggep editor sebagai lawan bicara yang setara, dan nulis dengan gaya yang nantangin template standar penulisan akademis.
Media Ikut Bersuara Soal Bias Publikasi Ilmiah
Prioritaskan Riset Lokal
Robby Irfany Maqoma, seorang Managing Editor, mengakui adanya bias di jurnal-jurnal ilmiah. Katanya, banyak ilmuwan yang nyoba berbagai cara biar studi mereka bisa terbit. “Menganggap negara berkembang ini tidak kompeten, bias-bias itu selalu ada,” ujarnya di sebuah acara di Jakarta (31 Oktober 2025). “Dan betul itu terjadi. Di Indonesia, teman-teman peneliti juga sering bercerita bahwa mereka itu kesusahan. Maka harus memakai afiliasi luar negeri, bahkan ada yang rela jadi visiting scholar walaupun tidak punya waktu demi memuluskan artikel mereka bisa terbit di jurnal bergengsi,” imbuhnya.
Diversifikasi Sumber Informasi
Tapi, Robby bilang kalau ada juga perlawanan dari dalam negeri, termasuk dari kalangan redaksi media. Caranya? Meningkatkan kualitas jurnal-jurnal Indonesia. “Ketika ada suatu penemuan, kita akan periksa dulu yang di Indonesia itu ada atau tidak. Biasanya, sepanjang metodenya bagus, transparan, kita akan pakai dari Indonesianya dulu, bukan dari luar, sepanjang itu relevan,” tuturnya. “Karena kita tidak mungkin cuma pakai satu jurnal sebagai satu bukti. Biasanya kita akan mencari jurnal-jurnal lain yang memang relevan. Dan kami selalu mengusahakan, usahakan supaya tidak dari satu jurnal saja. Jadi dibandingkan dengan jurnal yang lain bukan semata-mata pertimbangan bias itu saja, tetapi meragamkan narasumbernya,” imbuhnya.
Dia menganalogikan satu artikel ilmiah itu kayak satu bukti atau satu saksi di pengadilan. Butuh banyak bukti dan saksi biar argumennya kuat. “Jadi kita dudukkan setara saja di antara jurnal-jurnal kredibel di Indonesia. Kalau belum ada yang lain, kita tahan,” pungkasnya.
Intinya, diskriminasi dalam publikasi ilmiah ini masalah serius yang butuh perhatian dan solusi nyata. Dengan ngungkap bias yang tersembunyi dan ngedorong praktik publikasi yang lebih inklusif, kita bisa nyiptain ekosistem riset yang lebih adil dan representatif buat semua ilmuwan, tanpa peduli dari mana mereka berasal atau apa latar belakang budayanya. Cuma dengan cara ini, pengetahuan ilmiah yang dihasilkan bener-bener bisa nyerminin keberagaman pemikiran dan pengalaman manusia.




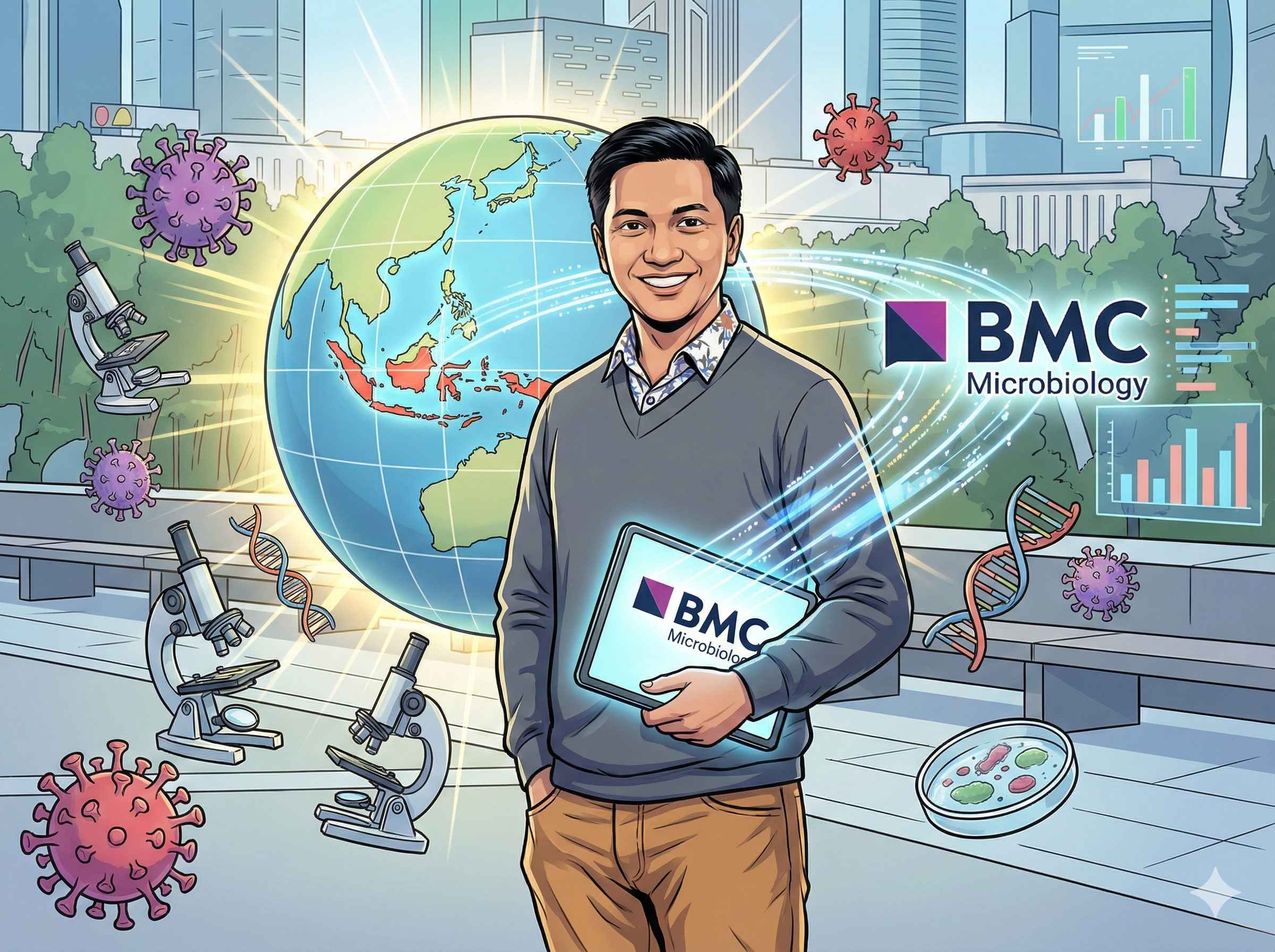




Leave a Comment